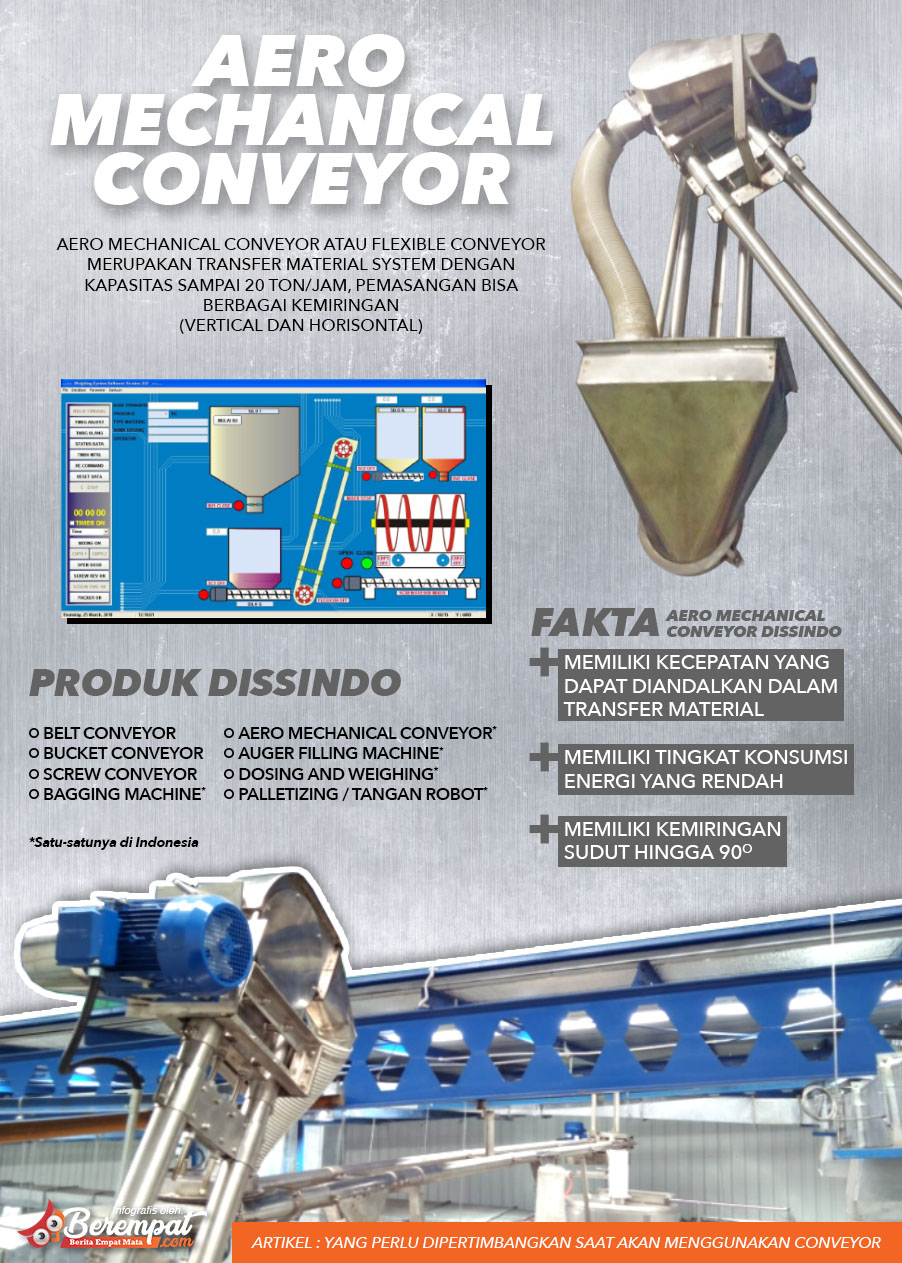Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen. Dengan demikian, BI tercatat telah mempertahankan suku bunga acuan 6 persen sejak 15 November 2018.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian berpendapat, kebijakan yang dijalankan oleh BI tersebut kurang tepat. BI mesti berani melakukan kebijakan ekspansif dengan menurunkan suku bunganya agar perkeonomian Indonesia bisa melaju lebih cepat.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% jika ingin terbebas dari kutukan ‘middle-income trap’. Saat ini, Indonesia beruntung dianugerahi oleh bonus demografi, kondisi dimana anak-anak mudanya atau generasi produktif masih lebih besar dibanding generasi tua. Namun, diprediksi bonus demografi ini akan berakhir pada 2060 yaitu ketika Indonesia akan memasuki masa yang dikenal dengan istilah ‘ageing population’ atau era dimana generasi milenial saat ini akan sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek,” jelasnya di acara diskusi online Indef bertema Kebijakan Moneter Pasca Pilpres, Minggu 28 April 2019.
Menurutnya, belajar dari negara lain seperti Jepang dan Korea maka Indonesia mesti mencapai pendapatan per kapita sekitar USD40.000 sebelum era bonus demografi ini berakhir. Saat ini, pendapatan per kapita masih sekitar $12.000. jadi, masih jauh sekali dari posisi ideal. Konsekuensinya, otoritas baik pemerintah dan BI mesti kerja lebih keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak stagnan di level 5% seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.
Peneliti Indef Rizal Taufikurrahman menambahkan berkaitan dengan kebijakan moneter, dimana BI tetap bertahan di suku bunga BI 7 day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga lending Facility 6.75%. Keputusan tersebut perlu dilihat lagi dampaknya terhadap kinerja ekonomi, khususnya kinerja investasi. Perlu dilihat juga dampak kebijakan moneter tsb terhadap kinerja industri, usaha kecil, menengah dan mikro.
“Nampaknya dari kebijakan tersebut, BI mengejar stabilitas pasar uang tanpa melihat efisiensi produksi dan kinerja sektor riil. Seharusnya BI mempertimbangkan dampak ke sektor riil yang akan mendorong produktivitas industri untuk memberikan nilai tambah terhadap Gross Domestic Product (GDP) nasional. Apalagi target GDP tahun ini 5.3%, artinya didorong dari sektor riil. Melalui kebijakan moneter yang ekspansif dengan penyesuaian suku bunga menjadi urgent. Selain itu, harus dilihat juga dengan kebijakan fiskal yang saling support. Harapannya efektivitas kebijakan moneter yang ditetapkan BI menjadi efektif,” tambahnya.
Ia menilai keputusan BI dengan kebijakan moneter tersebut perlu ditinjau ulang. Apakah menggairahkan kinerja sektor riil atau sebaliknya, terutama terhadap investasi yang semakin membaik. Apalagi tahun ini adalah tahun yang sangat tergantung pada sektor riil untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2019, yaitu 5.3%.
Dzulfian Syafrian menilai semakin tinggi suku bunga, semakin tergerus pula daya beli masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh semakin tinggi suku bunga acuan BI maka semakin tinggi pula suku bunga cicilan-cicilan lainnya, seperti KPR, cicilan motor, mobil, dan sebagainya. Sehingga, wajar kalau daya beli masyarakat belakangan merosot karena rupiah melemah dan BI rate ketinggian.
Wakil Direktur Indef, Eko Listyanto, mengatakan bahwa di sektor hilir berkaitan dengan inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan kelesuan daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok cenderung meningkat jelang puasa dan lebaran. Sementara, kebijakan kendali harga sejauh ini hanya dilakukan dengan cara tradisional (melalui operasi pasar) dan regulasi-regulasi (Harga Eceran Tertinggi, dan sebagainya) yang susah diimplementasikan secara optimal.
“Ada setidaknya 3 komoditas kontributor inflasi yang menjadi langganan di bulan Puasa dan Lebaran, sehingga perlu diwaspadai yaitu bahan makanan; makanan dan minuman Jadi; dan transportasi. Bahan makanan dan makanan jadi (beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur) menjadi pemicu inflasi pangan di 2018 lalu. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, komoditas-komoditas ini akan memicu inflasi lagi di tahun ini. Alarmnya sudah dimulai dari harga bawang putih (bumbu-bumbuan) dan daging ayam ras,” tambahnya.
Ia menambahkan ada satu hal yang disadari Pemerintah tapi lamban bereaksi adalah fenomena bahwa aspek geografi dalam pengendalian inflasi penting untuk dicermati. Hal ini karena 80% lebih persoalan pengendalian harga (inflasi) ada di luar Jakarta. Meskipun ada TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), tanpa upaya serius menangani inflasi di daerah, maka setiap jelang lebaran harga pangan akan selalu mengalami lonjakan.